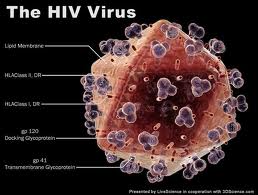BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Organ reproduksi membentuk apa yang dikenal sebagai traktus genitalis yang berkembang setelah traktus urinarius. Kelamin laki-laki maupun perempuan sejak lahir sudah dapat dikenal, sel produksi berkembang di sebelah depan ginjal yang tumbuh sebagai koloni-koloni sel kemudian membentuk kelenjar reproduksi. Perkembangan sifat terjadi pada umur 10-14 tahun. Perubahan penting terjadi pada usia remaja ketika jiwa dan raganya menjadi matang. Dalam pubertas anak tumbuh dengan cepat dan mendapatkan bentuk tubuh yang khas dengan jenisnya. Dengan pubertas ini wanita masuk dalam masa reproduktif, artinya masa mendapat keturunan yang berlangsung kira-kira 30 tahun. Pada laki-laki dewasa pubertas dimulai dengan perubahan suara lebih berat, pembesaran genitalia eksterna, tampilnya bulu di atas tubuh dan muka dan tumbuhnya jakun.
Pada pria pubertas sering terjadi ereksi akibat rangsangan seksual dan menghasilkan sperma sehingga terjadi mimpi basah sebagai akibat dari mimpi erotik. Hal itu mendorong hubungan seksual yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.
1.2 Tujuan
1.2.1 Untuk mengetahui alat-alat reproduksi pada pria beserta fungsinya.
1.2.2 Untuk mengetahui perkembangan alat-alat reproduksi pria.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Sistem Reproduksi
Organ reproduksi berkembang sangat menakjubkan. Testis pada pria maupun sel ovarium pada wanita mulai tumbuh pada awal kehidupan janin, tetapi sifat kelamin belum dikenal. Sel reproduksi berkembang di sebelah depan ginjal kemudian membentuk kelenjar reproduksi yang berisi sel benih dan membentuk struktur sekelilingnya. Organ reproduksi disebut traktus genitalis yang berhubungan dengan traktus urinarius, tetapi tidak bersambung. Sebagian besar organ reproduksi terletak di luar pelvis. Traktus genitalis pada perempuan bersambung dengan rongga peritoneum yang terletak dalam rongga panggul kecil.
2.2 Organ Reproduksi Pria
Organ reproduksi pria tidak terpisah dari saluran uretra dan sejajar dengan kelamin luar. Organ reproduksi pria terdiri dari kelenjar (terdiri dari : testis, vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbo uretralis), duktus atau saluran (epididimis, duktus seminalis, uretra) dan bangun penyambung (skrotum, fenikulus spermatikus, dan penis).
2.2.1 Kelenjar
a. Testis
Organ ini merupakan 2 buah glandula yang memproduksi semen, terdapat di dalam skrotum yang digantung oleh fenukulus spermatikus. Pada bayi dalam kandungan, testis terdapat dalam kavum abdominalis di belakang peritonium, sebelum kelahiran akan turun ke kanalis inguinalis bersama dengan fenikulus sperma tikus kemudian masuk ke dalam skrotum. Testis merupakan tempat dibentuknya spermatozoa dan hormon pria yang terdiri dari belahan-belahan, disebut lobulus testis yang menghasilkan hormon testosteron dan menimbulkan sifat
kejantanan, terjadi setelah masa pubertas, di samping itu, follicle stimulating hormon (FSH) dan lutein hormon (LH).
b. Pembungkus testis
1) Fasia spermatika eksterna. Suatu membran yang tipis, memanjang ke arah bawah di antara venikulus dan testis, berakhir pada cincin subkutan inguinalis.
2) Lapisan kremasterika, terdiri dari selapis otot. Lapisan ini sesuai dengan m.obligus abdominis internus dan cascies abdominus internus.
3) Fasies spermatika interna. Suatu membran tipis dan menutupi fenikulus spermatikus. Fasia ini akan berakhir pada cincin inguinalis interna bersama dengan fasia transfersalis. Lapisan ini sesuai dengan m.obligus abdominis internus dan fasianya.
c. Pembuluh darah testis
1) Arteri pudenda eksterna pars superfisialis merupakan cabang dari arteri femoralis.
2) Arteri perinealis superfisialis merupakan cabang dari a.pudenda interna.
3) Arteri kremasterika merupakan cabang dari a.epigastrika inferior.
4) Untuk pembuluh darah vena mengikuti arteri.
d. Persarafan testis
1) N. Ilioinguinalis
2) N. Lumbo inguinalis cabang dari pleksus lumbalis.
3) N. Perinealis pars superfisialis.
e. Vesika seminalis
Vesika seminalis merupakan dua ruangan di antara fundus vesika urinaria dan rektum yang masing-masing ruangan berbentuk piramid, permukaan anterior berhubungan dengan fundus vesika urinaria, dan permukaan posterior terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fasia rektovesikalis.
Panjang kelenjar ini 5 – 10 cm dan merupakan kelenjar sekresi menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktosa dan zat gizi (prostaglandin dan fibrinogen) yang merupakan sumber energi bagi spermatozoa. Vesika seminalis bermuara pada duktus deferens dan bergabung dengan duktus ferens. Penggabungan ini disebut duktus ejakulatorius. Sekresi vesika seminalis disebut semen sebagai pelindung spermatozoa. Selama ejakulasi, vesika seminalis mengosongkan isinya ke dalam duktus ejakulatorius sehingga menambah semen ejakulasi serta mukosa. Duktus ejakulatorius berjumlah dua buah. Pada sisi lain dari garis tengah, masing-masing duktus akan membentuk gabungan vesikula seminalis dengan duktus deferens, panjangnya 2 cm, mulai dari basis glandula prostat berjalan ke depan bawah di antara lobus medialis lateralis, dan dari utrikulus prostatikus berakhir ke dalam pinggir urtikulus.
f. Pembuluh darah dan saraf
Arteri yang menyuplai vesika seminalis adalah cabang dari a.vesikalis medialis, a.vesikalis inferior dan a.haemorrhoidalis medialis. Vena-vena dan sistem limfe menyertai arteri. Persarafan merupakan cabang dari pleksus pelvikus
g. Glandula prosfat
Sebagian glandula prostat bersifat glandular dan sebagian lagi bersifat otot, terdapat di bawah orifisium uretra interna dan sekeliling permukaan uretra, dan melekat di bawah vesika urinaria dalam rongga pelvis di bawah posterior simfisis pubis. Prostat merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus (lobus posterior, anterior, lateral dan medial). Fungsi kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan alkali yang encer, seperti susu mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra.
Basis prostat menghadap ke atas, berhubungan dengan permukaan inferior vesika urinaria, permukaannya berhubungan dengan vesika urinaria, dan mengarah ke bawah dan berhubungan dengan diafragma urogenitalis. Prostat dipertahankan posisinya oleh ligamentum puboprostatika, lapisan dalam diafragma urogenitalis, m.levator ani pars anterior, dan m. Levator prostat bagian dari m.levator ani.
h. Pembuluh darah dan saraf
1) A.pudenda interna
2) A.cesicalis inferior
3) A.Haemorrhoidalis medialis
Vena akan membentuk pleksus di sekitar sisi dan basis glandula prostat dan berakhir di vena hipogastrika. Nervus merupakan cabang dari pleksus pelvis.
i. Kelenjar bulbo uretralis
Kelenjar ini terdapat di belakang lateral pars memranasea uretra, di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah kelenjar prostat. Bentuknya bundar, kecil dan warnanya kuning, panjangnya 2,5 cm, dan fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat. Kelenjar bulbo uretralis dibungkus oleh simpai jaringan ikat tipis yang di luarnya terdapat serat-serat otot rangka. Jaringan ikatnya banyak mengandung serat elastin, serat otot rangka, dan serat otot polos.
2.2.2 Duktus
a. Skrotum
Skrotum merupakan sepasang kantong yang menggantung di dasar pelvis. Di depan skrotum terdapat penis dan di belakangnya ada anus. Skrotum atau kandung buah pelir berupa kantong yang terdiri dari kulit tanpa lemak yang memiliki sedikit jaringan otot dan berada di dalam pembungkus yang disebut tunika vaginalis. Tunika vaginalis dibentuk
dari peritonium skrotum yang banyak mengandung pigmen, di dalamnya terdapat kantong-kantong. Setiap kantong berisi epididimis feniculus spermatikus. Skrotum kiri tergantung lebih rendah dari skrotum kanan. Skrotum bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya pengaruh panas dan orang tua. Pada keadaan lemah, skrotum akan memanjang dan lemas, sedangkan dalam keadaan dingin akan memendek dan berkerut. Skrotum terdiri dari dua lapisan, yaitu kulit dan tunika dartos.
1) Kulit, warna kecoklatan, tipis, dan mempunyai filica/rugae, terdapat folikel sebasea yang di kelilingi oleh rambut keriting yang akarnya terlihat melalui kulit.
2) Tunika dartos berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skrotum. Tunika dartos ini membentuk septum yang membagi skrotum menjadi dua ruangan untuk testis dan terdapat di bawah permukaan penis.
Pada skrotum terdapat m.kremaster yang muncul dari m.obliques internus abdominalis yang menggantungkan testis dan mengangkat testis menurut kemauan dan refleks ejakulasi.
b. Fenikulus spermatikus
Fenikulus spermatikus merupakan bangun penyambung yang berisi duktus seminalis, pembuluh limfe, dan serabut saraf. Bentuknya memanjang dari abdominalis inguinalis dan tersusun konvergen ke bagian belakang testis, melewati cincin subkutan dan turun hampir vertikal ke skrotum. Fenikulus spermatikus kiri lebih panjang dari yang kanan karena testis kiri tergantung lebih rendah dari testis kanan.
c. Pembuluh darah fenikulus spermatikus
1) Arteri spermatika interna, merupakan cabang aorta abdominalis, keluar dari abdomen melalui cincin inguinalis abdominalis dan bergabung dengan fenikulus spermatikus sepanjang kanalis
inguinalis yang memberikan darah untuk epididimis dan subtansia testis.
2) Arteri spermatika eksterna, merupakan cabang dari a.epigastrika inferior yang berfungsi memberikan darah untuk fenikulus spermatikus beranastomosis dengan a.spermatika interna.
3) Arteri duktus deferens merupakan cabang dari a.fesikalis inferior, bentuknya panjang dan bergabung dengan duktus deferens beranatomosis dengan a.spermatika interna di dekat testis.
4) V. Permatika, mulai dari belakang testis, menerima darah dari epididimis, membentuk pompa, bagian dari fenikulus spermatikus. Pembuluh-pembuluh yang membentuk pleksus banyak masuk sepanjang fenikulus spermatikus di depan duktus diferens. Di bawah cincin substansia inguinalis, pembuluh ini bersatu membentuk 2-4 vena, lewat kanalis inguinalis masuk ke abdomen. Melalui cincin inguinalis abdominalis, yang kanan bermuara ke vena kava inferior dan yang kiri bermuara ke vena renalis sinistra.
d. Pembuluh limfe
Pembulh limfe terdiri dari dua bagian, yaitu permukaan luar dan permukaan dalam. Pembuluh limfe berasal dari permukaan tunika vaginalis epididimis dan korpus testis. Pembuluh ini akan membentuk 4-8 traktus dan berakhir pada bagian lateral dari pronatik dan nervus lumbalis II.
e. Pembuluh saraf
Pleksus spermatikus merupakan saraf simpatis yang bergabung dengan cabang dari pleksus pelvis yang menyertai arteri duktus deferens.
f. Penis
Bagian ini terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujungnya disebut glans penis, bagian tengah disebut korpus penis, dan bagian pangkal disebut radiks penis. Kulit ini berhubungan dengan pelvis, skrotum dan perineum. Kulit pembungkus amat tipis dan tidak
berhubungan dengan bagian permukaan dalam organ dan tidak mempunyai jaringan adiposa. Di belakang orifisium uretra eksterna, kulit ini membentuk perlipatan kecil yang disebut frenulus preputium. Kulit yang menutupi glans penis bersambung dengan membran mukosa uretra pada orifisium dan tidak mempunyai rambut. Prepusium yang menutupi glans dipisahkan dari prepusium dan didalamnya terdapat ruangan yang dangkal.
1) Fasia superfisialis : secara langsung berhubungan dengan fasia skrotum dengan lapisan sel otot polos. Di antara fasia superfisialis dan profunda terdapat celah yang menyebabkan kulit bergerak bebas. Pada bagian anterior ujung m.bulbokavernosus dan m.iskhiakavernosus terbelah menjadi lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan luar menutupi permukaan superior otot-otot ini dan fasia perinealis dari perineum. Lapisan dalam merupakan lanjutan fasia penis dan lamina profunda. Fasia profunda dari penis menutupi organ dengan kapsul yang kuat.
2) Korpora kavernosa penis : terdiri dari dua masa silinder yang erektil, terdiri dari ¾ dari bagian anterior batang penis. Pada simpisis pubis bagian posterior secara berangsur-angsur membentuk bangun yang lonjong. Korpora kavernosus penis ditutupi oleh kapsul yang kuat, terdiri dari benang-benang superfisialis dan profunda yang mempunyai arah longitudinal dan membentuk satu saluran yang masing-masing mengelilingi korpora dan membentuk satu saluran yang masing-masing mengelilingi korpora dan membentuk septum penis. Septum ini tebal dan terdiri dari bangunan vertikal yang disebut septum pektini formis. Pada permukaan atas terdapat celah kecil tempat v. Dorsalis penis profunda dan pada permukaan bawah terdapat celah yang dalam dan luas berisi korpus kavernosa uretra. Bagian anterior korpus kavernosa penis akan melebar dan disebut bulbus korpus kavernosa penis. Bagian ini terikat kuat pada ramus iskhium pubis yang ditutupi oleh m.iskhium kavernosus.
3) Korpus kavernosa uretra merupakan bagian penis yang berisi uretra, di dalam batang penis berbentuk silinder yang lebih kecil dari kavernosa penis, pada ujungnya agak melebar, bagian anterior membentuk glans penis dan posterior membentuk bulbus uretra.
4) Glans penis merupakan bagian akhir anterior korpus kavernosa uretra yang memanjang ke dalam, bentuknya seperti jamur. Glans penis ini licin dan kuat, bagian perifer lebih besar hingga membentuk pinggir yang bundar yang disebut koronaglandis. Bagian perifer menyempit membentuk bulbus retroglandularis dari leher penis dan pada puncak glans penis terdapat celah dari orifisium uretra eksterna.
5) Bulbus uretra : merupakan pembesaran bagian posterior, 3-4 cm, dari korpus kavernosa uretra dan letaknya superfisialis dari diafragma urogenitas. Fasia superfisialis bercampur dengan kapsula fibrosa dan disebut ligamentum bulbus yang ditutupi oleh fasia bulbus kavernosus.
g. Penggantung penis
1) Ligamentum fundiformis penis, lapisan tebal yang berasal dari fasia superfisialis dari dinding abdominalis anterior di atas pubis.
2) Ligamentum suspensorium penis, berupa benang berbentuk segitiga, bagian eksterna dari fasia profunda menggantung dorsum dan akar penis ke bagian inferior linea alba. Simfisis pubis dan ligamentum arquarta pubis, kruris ischio pubis dan bulbu diafragma urogenitalis merupakan alat penggantung penis.
h. Pembuluh darah penis
1) Arteri pudenda interna, merupakan cabang a.hipogastrika yang menyuplai darah untuk ruangan kavernosus.
2) Arteri profunda penis, merupakan cabang dari a.dorsalis penis. Bercabang terbuka langsung ke ruangan kavernosa. Cabang kapilernya menyuplai darah ke trabekula di ruangan kavernosa, dikembalikan ke vena pada dorsum dan membentuk vena dorsalis
penis yang melewati permukaan superrior korpora kavernosa dan bergabung dengan vena yang lain.
i. Carian semen
Cairan semen terdiri dari spermatozoa dan cairan yang dihasilkan oleh seluruh kelenjar kelamin, serta sedikit tambahan yang berasal dari sistem saluran kelamin. Semen merupakan cairan keruh keputihan yang mengandung 100 juta/ml spermatozoa dan jumlahnya sangat bervariasi. Setiap ejakulasi mengeluarkan 3 ml (300 juta spermatozoa). Pengeluaran semen berlangsung dalam urutan tertentu. Kelenjar bulbo uretralis dan kelenjar uretra mengeluarkan sekret berupa lendir ketika ereksi dan akan melumasi uretra paras kavernosa sewaktu ejakulasi kelenjar prostat bersekresi lebih dahulu. Sekretnya bersifat basa dan menurunkan keasaman uretra yang mengandung sisa air kemih kemudian disusul oleh spermatozoa yang diperas ke luar dari duktus epididimis dan duktus deferens melalui kontraksi dinding otot. Akhirnya, sekresi kental dari vesikula seminalis mengandung fruktosa dan bahan makanan bagi sperma ditambahkan ke dalam massa tersebut.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Organ reproduksi membentuk apa yang dikenal sebagai traktus genitalis yang berkembang setelah traktus urinarius. Kelamin laki-laki maupun perempuan sejak lahir sudah dapat dikenal, sel produksi berkembang di sebelah depan ginjal yang tumbuh sebagai koloni-koloni sel kemudian membentuk kelenjar reproduksi. Perkembangan sifat terjadi pada umur 10-14 tahun. Perubahan penting terjadi pada usia remaja ketika jiwa dan raganya menjadi matang. Dalam pubertas anak tumbuh dengan cepat dan mendapatkan bentuk tubuh yang khas dengan jenisnya. Dengan pubertas ini wanita masuk dalam masa reproduktif, artinya masa mendapat keturunan yang berlangsung kira-kira 30 tahun. Pada laki-laki dewasa pubertas dimulai dengan perubahan suara lebih berat, pembesaran genitalia eksterna, tampilnya bulu di atas tubuh dan muka dan tumbuhnya jakun.
Pada pria pubertas sering terjadi ereksi akibat rangsangan seksual dan menghasilkan sperma sehingga terjadi mimpi basah sebagai akibat dari mimpi erotik. Hal itu mendorong hubungan seksual yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.
1.2 Tujuan
1.2.1 Untuk mengetahui alat-alat reproduksi pada pria beserta fungsinya.
1.2.2 Untuk mengetahui perkembangan alat-alat reproduksi pria.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Sistem Reproduksi
Organ reproduksi berkembang sangat menakjubkan. Testis pada pria maupun sel ovarium pada wanita mulai tumbuh pada awal kehidupan janin, tetapi sifat kelamin belum dikenal. Sel reproduksi berkembang di sebelah depan ginjal kemudian membentuk kelenjar reproduksi yang berisi sel benih dan membentuk struktur sekelilingnya. Organ reproduksi disebut traktus genitalis yang berhubungan dengan traktus urinarius, tetapi tidak bersambung. Sebagian besar organ reproduksi terletak di luar pelvis. Traktus genitalis pada perempuan bersambung dengan rongga peritoneum yang terletak dalam rongga panggul kecil.
2.2 Organ Reproduksi Pria
Organ reproduksi pria tidak terpisah dari saluran uretra dan sejajar dengan kelamin luar. Organ reproduksi pria terdiri dari kelenjar (terdiri dari : testis, vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbo uretralis), duktus atau saluran (epididimis, duktus seminalis, uretra) dan bangun penyambung (skrotum, fenikulus spermatikus, dan penis).
2.2.1 Kelenjar
a. Testis
Organ ini merupakan 2 buah glandula yang memproduksi semen, terdapat di dalam skrotum yang digantung oleh fenukulus spermatikus. Pada bayi dalam kandungan, testis terdapat dalam kavum abdominalis di belakang peritonium, sebelum kelahiran akan turun ke kanalis inguinalis bersama dengan fenikulus sperma tikus kemudian masuk ke dalam skrotum. Testis merupakan tempat dibentuknya spermatozoa dan hormon pria yang terdiri dari belahan-belahan, disebut lobulus testis yang menghasilkan hormon testosteron dan menimbulkan sifat
kejantanan, terjadi setelah masa pubertas, di samping itu, follicle stimulating hormon (FSH) dan lutein hormon (LH).
b. Pembungkus testis
1) Fasia spermatika eksterna. Suatu membran yang tipis, memanjang ke arah bawah di antara venikulus dan testis, berakhir pada cincin subkutan inguinalis.
2) Lapisan kremasterika, terdiri dari selapis otot. Lapisan ini sesuai dengan m.obligus abdominis internus dan cascies abdominus internus.
3) Fasies spermatika interna. Suatu membran tipis dan menutupi fenikulus spermatikus. Fasia ini akan berakhir pada cincin inguinalis interna bersama dengan fasia transfersalis. Lapisan ini sesuai dengan m.obligus abdominis internus dan fasianya.
c. Pembuluh darah testis
1) Arteri pudenda eksterna pars superfisialis merupakan cabang dari arteri femoralis.
2) Arteri perinealis superfisialis merupakan cabang dari a.pudenda interna.
3) Arteri kremasterika merupakan cabang dari a.epigastrika inferior.
4) Untuk pembuluh darah vena mengikuti arteri.
d. Persarafan testis
1) N. Ilioinguinalis
2) N. Lumbo inguinalis cabang dari pleksus lumbalis.
3) N. Perinealis pars superfisialis.
e. Vesika seminalis
Vesika seminalis merupakan dua ruangan di antara fundus vesika urinaria dan rektum yang masing-masing ruangan berbentuk piramid, permukaan anterior berhubungan dengan fundus vesika urinaria, dan permukaan posterior terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fasia rektovesikalis.
Panjang kelenjar ini 5 – 10 cm dan merupakan kelenjar sekresi menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktosa dan zat gizi (prostaglandin dan fibrinogen) yang merupakan sumber energi bagi spermatozoa. Vesika seminalis bermuara pada duktus deferens dan bergabung dengan duktus ferens. Penggabungan ini disebut duktus ejakulatorius. Sekresi vesika seminalis disebut semen sebagai pelindung spermatozoa. Selama ejakulasi, vesika seminalis mengosongkan isinya ke dalam duktus ejakulatorius sehingga menambah semen ejakulasi serta mukosa. Duktus ejakulatorius berjumlah dua buah. Pada sisi lain dari garis tengah, masing-masing duktus akan membentuk gabungan vesikula seminalis dengan duktus deferens, panjangnya 2 cm, mulai dari basis glandula prostat berjalan ke depan bawah di antara lobus medialis lateralis, dan dari utrikulus prostatikus berakhir ke dalam pinggir urtikulus.
f. Pembuluh darah dan saraf
Arteri yang menyuplai vesika seminalis adalah cabang dari a.vesikalis medialis, a.vesikalis inferior dan a.haemorrhoidalis medialis. Vena-vena dan sistem limfe menyertai arteri. Persarafan merupakan cabang dari pleksus pelvikus
g. Glandula prosfat
Sebagian glandula prostat bersifat glandular dan sebagian lagi bersifat otot, terdapat di bawah orifisium uretra interna dan sekeliling permukaan uretra, dan melekat di bawah vesika urinaria dalam rongga pelvis di bawah posterior simfisis pubis. Prostat merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus (lobus posterior, anterior, lateral dan medial). Fungsi kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan alkali yang encer, seperti susu mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra.
Basis prostat menghadap ke atas, berhubungan dengan permukaan inferior vesika urinaria, permukaannya berhubungan dengan vesika urinaria, dan mengarah ke bawah dan berhubungan dengan diafragma urogenitalis. Prostat dipertahankan posisinya oleh ligamentum puboprostatika, lapisan dalam diafragma urogenitalis, m.levator ani pars anterior, dan m. Levator prostat bagian dari m.levator ani.
h. Pembuluh darah dan saraf
1) A.pudenda interna
2) A.cesicalis inferior
3) A.Haemorrhoidalis medialis
Vena akan membentuk pleksus di sekitar sisi dan basis glandula prostat dan berakhir di vena hipogastrika. Nervus merupakan cabang dari pleksus pelvis.
i. Kelenjar bulbo uretralis
Kelenjar ini terdapat di belakang lateral pars memranasea uretra, di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah kelenjar prostat. Bentuknya bundar, kecil dan warnanya kuning, panjangnya 2,5 cm, dan fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat. Kelenjar bulbo uretralis dibungkus oleh simpai jaringan ikat tipis yang di luarnya terdapat serat-serat otot rangka. Jaringan ikatnya banyak mengandung serat elastin, serat otot rangka, dan serat otot polos.
2.2.2 Duktus
a. Skrotum
Skrotum merupakan sepasang kantong yang menggantung di dasar pelvis. Di depan skrotum terdapat penis dan di belakangnya ada anus. Skrotum atau kandung buah pelir berupa kantong yang terdiri dari kulit tanpa lemak yang memiliki sedikit jaringan otot dan berada di dalam pembungkus yang disebut tunika vaginalis. Tunika vaginalis dibentuk
dari peritonium skrotum yang banyak mengandung pigmen, di dalamnya terdapat kantong-kantong. Setiap kantong berisi epididimis feniculus spermatikus. Skrotum kiri tergantung lebih rendah dari skrotum kanan. Skrotum bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya pengaruh panas dan orang tua. Pada keadaan lemah, skrotum akan memanjang dan lemas, sedangkan dalam keadaan dingin akan memendek dan berkerut. Skrotum terdiri dari dua lapisan, yaitu kulit dan tunika dartos.
1) Kulit, warna kecoklatan, tipis, dan mempunyai filica/rugae, terdapat folikel sebasea yang di kelilingi oleh rambut keriting yang akarnya terlihat melalui kulit.
2) Tunika dartos berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skrotum. Tunika dartos ini membentuk septum yang membagi skrotum menjadi dua ruangan untuk testis dan terdapat di bawah permukaan penis.
Pada skrotum terdapat m.kremaster yang muncul dari m.obliques internus abdominalis yang menggantungkan testis dan mengangkat testis menurut kemauan dan refleks ejakulasi.
b. Fenikulus spermatikus
Fenikulus spermatikus merupakan bangun penyambung yang berisi duktus seminalis, pembuluh limfe, dan serabut saraf. Bentuknya memanjang dari abdominalis inguinalis dan tersusun konvergen ke bagian belakang testis, melewati cincin subkutan dan turun hampir vertikal ke skrotum. Fenikulus spermatikus kiri lebih panjang dari yang kanan karena testis kiri tergantung lebih rendah dari testis kanan.
c. Pembuluh darah fenikulus spermatikus
1) Arteri spermatika interna, merupakan cabang aorta abdominalis, keluar dari abdomen melalui cincin inguinalis abdominalis dan bergabung dengan fenikulus spermatikus sepanjang kanalis
inguinalis yang memberikan darah untuk epididimis dan subtansia testis.
2) Arteri spermatika eksterna, merupakan cabang dari a.epigastrika inferior yang berfungsi memberikan darah untuk fenikulus spermatikus beranastomosis dengan a.spermatika interna.
3) Arteri duktus deferens merupakan cabang dari a.fesikalis inferior, bentuknya panjang dan bergabung dengan duktus deferens beranatomosis dengan a.spermatika interna di dekat testis.
4) V. Permatika, mulai dari belakang testis, menerima darah dari epididimis, membentuk pompa, bagian dari fenikulus spermatikus. Pembuluh-pembuluh yang membentuk pleksus banyak masuk sepanjang fenikulus spermatikus di depan duktus diferens. Di bawah cincin substansia inguinalis, pembuluh ini bersatu membentuk 2-4 vena, lewat kanalis inguinalis masuk ke abdomen. Melalui cincin inguinalis abdominalis, yang kanan bermuara ke vena kava inferior dan yang kiri bermuara ke vena renalis sinistra.
d. Pembuluh limfe
Pembulh limfe terdiri dari dua bagian, yaitu permukaan luar dan permukaan dalam. Pembuluh limfe berasal dari permukaan tunika vaginalis epididimis dan korpus testis. Pembuluh ini akan membentuk 4-8 traktus dan berakhir pada bagian lateral dari pronatik dan nervus lumbalis II.
e. Pembuluh saraf
Pleksus spermatikus merupakan saraf simpatis yang bergabung dengan cabang dari pleksus pelvis yang menyertai arteri duktus deferens.
f. Penis
Bagian ini terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujungnya disebut glans penis, bagian tengah disebut korpus penis, dan bagian pangkal disebut radiks penis. Kulit ini berhubungan dengan pelvis, skrotum dan perineum. Kulit pembungkus amat tipis dan tidak
berhubungan dengan bagian permukaan dalam organ dan tidak mempunyai jaringan adiposa. Di belakang orifisium uretra eksterna, kulit ini membentuk perlipatan kecil yang disebut frenulus preputium. Kulit yang menutupi glans penis bersambung dengan membran mukosa uretra pada orifisium dan tidak mempunyai rambut. Prepusium yang menutupi glans dipisahkan dari prepusium dan didalamnya terdapat ruangan yang dangkal.
1) Fasia superfisialis : secara langsung berhubungan dengan fasia skrotum dengan lapisan sel otot polos. Di antara fasia superfisialis dan profunda terdapat celah yang menyebabkan kulit bergerak bebas. Pada bagian anterior ujung m.bulbokavernosus dan m.iskhiakavernosus terbelah menjadi lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan luar menutupi permukaan superior otot-otot ini dan fasia perinealis dari perineum. Lapisan dalam merupakan lanjutan fasia penis dan lamina profunda. Fasia profunda dari penis menutupi organ dengan kapsul yang kuat.
2) Korpora kavernosa penis : terdiri dari dua masa silinder yang erektil, terdiri dari ¾ dari bagian anterior batang penis. Pada simpisis pubis bagian posterior secara berangsur-angsur membentuk bangun yang lonjong. Korpora kavernosus penis ditutupi oleh kapsul yang kuat, terdiri dari benang-benang superfisialis dan profunda yang mempunyai arah longitudinal dan membentuk satu saluran yang masing-masing mengelilingi korpora dan membentuk satu saluran yang masing-masing mengelilingi korpora dan membentuk septum penis. Septum ini tebal dan terdiri dari bangunan vertikal yang disebut septum pektini formis. Pada permukaan atas terdapat celah kecil tempat v. Dorsalis penis profunda dan pada permukaan bawah terdapat celah yang dalam dan luas berisi korpus kavernosa uretra. Bagian anterior korpus kavernosa penis akan melebar dan disebut bulbus korpus kavernosa penis. Bagian ini terikat kuat pada ramus iskhium pubis yang ditutupi oleh m.iskhium kavernosus.
3) Korpus kavernosa uretra merupakan bagian penis yang berisi uretra, di dalam batang penis berbentuk silinder yang lebih kecil dari kavernosa penis, pada ujungnya agak melebar, bagian anterior membentuk glans penis dan posterior membentuk bulbus uretra.
4) Glans penis merupakan bagian akhir anterior korpus kavernosa uretra yang memanjang ke dalam, bentuknya seperti jamur. Glans penis ini licin dan kuat, bagian perifer lebih besar hingga membentuk pinggir yang bundar yang disebut koronaglandis. Bagian perifer menyempit membentuk bulbus retroglandularis dari leher penis dan pada puncak glans penis terdapat celah dari orifisium uretra eksterna.
5) Bulbus uretra : merupakan pembesaran bagian posterior, 3-4 cm, dari korpus kavernosa uretra dan letaknya superfisialis dari diafragma urogenitas. Fasia superfisialis bercampur dengan kapsula fibrosa dan disebut ligamentum bulbus yang ditutupi oleh fasia bulbus kavernosus.
g. Penggantung penis
1) Ligamentum fundiformis penis, lapisan tebal yang berasal dari fasia superfisialis dari dinding abdominalis anterior di atas pubis.
2) Ligamentum suspensorium penis, berupa benang berbentuk segitiga, bagian eksterna dari fasia profunda menggantung dorsum dan akar penis ke bagian inferior linea alba. Simfisis pubis dan ligamentum arquarta pubis, kruris ischio pubis dan bulbu diafragma urogenitalis merupakan alat penggantung penis.
h. Pembuluh darah penis
1) Arteri pudenda interna, merupakan cabang a.hipogastrika yang menyuplai darah untuk ruangan kavernosus.
2) Arteri profunda penis, merupakan cabang dari a.dorsalis penis. Bercabang terbuka langsung ke ruangan kavernosa. Cabang kapilernya menyuplai darah ke trabekula di ruangan kavernosa, dikembalikan ke vena pada dorsum dan membentuk vena dorsalis
penis yang melewati permukaan superrior korpora kavernosa dan bergabung dengan vena yang lain.
i. Carian semen
Cairan semen terdiri dari spermatozoa dan cairan yang dihasilkan oleh seluruh kelenjar kelamin, serta sedikit tambahan yang berasal dari sistem saluran kelamin. Semen merupakan cairan keruh keputihan yang mengandung 100 juta/ml spermatozoa dan jumlahnya sangat bervariasi. Setiap ejakulasi mengeluarkan 3 ml (300 juta spermatozoa). Pengeluaran semen berlangsung dalam urutan tertentu. Kelenjar bulbo uretralis dan kelenjar uretra mengeluarkan sekret berupa lendir ketika ereksi dan akan melumasi uretra paras kavernosa sewaktu ejakulasi kelenjar prostat bersekresi lebih dahulu. Sekretnya bersifat basa dan menurunkan keasaman uretra yang mengandung sisa air kemih kemudian disusul oleh spermatozoa yang diperas ke luar dari duktus epididimis dan duktus deferens melalui kontraksi dinding otot. Akhirnya, sekresi kental dari vesikula seminalis mengandung fruktosa dan bahan makanan bagi sperma ditambahkan ke dalam massa tersebut.
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Organ utama reproduksi pada pria adalah testis. Fungsi testis :
1. Membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa dilakukan di tubulus seminiferus.
2. Menghasilkan hormon testosteron, dilakukan oleh sel interstisial.
Setelah pembentukan tubulus seminiferus, sperma masuk ke semini ferus selama 18 jam sampai 10 hari hingga mengalami proses pematangan. Fungsi testoteron :
1. Efek desensus testis.
2. Perkembangan seksual primer dan sekunder.
3.2 Saran
Seperti kata pepatah ”Tak ada gading yang tak retak”. Dalam pembuatan makalah ini tentu masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dari para pembaca demi kesempurnaan di masa yang akan datang.
3.1 Kesimpulan
Organ utama reproduksi pada pria adalah testis. Fungsi testis :
1. Membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa dilakukan di tubulus seminiferus.
2. Menghasilkan hormon testosteron, dilakukan oleh sel interstisial.
Setelah pembentukan tubulus seminiferus, sperma masuk ke semini ferus selama 18 jam sampai 10 hari hingga mengalami proses pematangan. Fungsi testoteron :
1. Efek desensus testis.
2. Perkembangan seksual primer dan sekunder.
3.2 Saran
Seperti kata pepatah ”Tak ada gading yang tak retak”. Dalam pembuatan makalah ini tentu masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dari para pembaca demi kesempurnaan di masa yang akan datang.